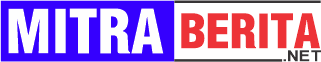DI pesisir Desa Pantai Balai, Kecamatan Seruway, Kabupaten Aceh Tamiang, sebuah tradisi kuno dan penuh makna terus hidup dan berkembang. Kenduri tolak bala, yang dilaksanakan setiap Rabu terakhir pada bulan Safar—dikenal dengan sebutan “Rabu Habis”—merupakan ritual tahunan yang menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat setempat.
Ritual ini merupakan bentuk kearifan lokal yang diwariskan secara turun-temurun. Dalam suasana sore yang hangat, di bawah langit yang mulai memerah, ratusan warga berkumpul dengan penuh semangat. Suara deburan ombak dan alunan doa-doa tradisional menciptakan simfoni alam yang khas. Aroma dupa dan kemenyan menyebar, mengantar saya pada perjalanan waktu yang membayangkan bagaimana nenek moyang masyarakat ini memulai tradisi ini. Apakah karena ketakutan akan murka alam, ataukah sebagai ungkapan syukur atas limpahan rezeki dari laut?
Sarah, salah seorang warga, menjelaskan dengan mata berbinar, “Tolak bala ini bukan hanya tentang meminta keselamatan. Ini tentang bagaimana kami menghargai alam, menjaga keseimbangan, dan mempererat tali persaudaraan.” Dalam kegelapan malam yang diterangi obor, suasana tersebut menggambarkan nilai-nilai kebersamaan yang masih kuat dalam masyarakat ini.
Setiap warga, dari anak-anak hingga orang tua, memiliki peran dalam ritual ini. Tradisi ini melibatkan seluruh lapisan masyarakat, menciptakan rasa persatuan yang mendalam. Namun, di tengah kemeriahan tersebut, tantangan juga terlihat. Beberapa pemuda tampak sibuk dengan ponsel mereka, mengambil foto dan video untuk media sosial. Akankah esensi ritual ini tersingkir oleh modernisasi?
Kekhawatiran ini dijawab oleh Lena, seorang warga setempat. “Kami sadar pentingnya melestarikan tradisi ini, tetapi kami juga ingin membuatnya lebih relevan dengan zaman. Tahun ini, kami mulai menggunakan media sosial untuk mengedukasi masyarakat luas tentang makna di balik ritual ini,” ujarnya.
Upaya ini menunjukkan bahwa komunitas ini tidak hanya mempertahankan tradisi, tetapi juga beradaptasi dengan perubahan zaman.
Kenduri tolak bala dimulai dengan pembacaan doa oleh tokoh agama setempat, dilanjutkan dengan penyembelihan hewan, dan diakhiri dengan makan bersama. Seluruh proses—mulai dari memasak hidangan hingga menyiapkan tempat—melibatkan kerja sama yang erat antar warga. Kaum ibu menyiapkan makanan, sementara kaum bapak mempersiapkan tempat dan sarana pendukung.
Salah satu ritual yang paling mencolok adalah melarung sesaji ke laut. Berbagai makanan, buah-buahan, dan kue tradisional diletakkan di atas rakit dan dihanyutkan ke laut sebagai bentuk penghormatan kepada penguasa laut. Sarah menjelaskan, “Melarung sesaji ini simbol penghormatan kami pada penguasa laut. Kami berharap para nelayan akan selalu diberi keselamatan dan hasil tangkapan yang melimpah.”
Tradisi ini bukan hanya tentang kepercayaan, tetapi juga tentang menjaga warisan budaya dan kearifan lokal. Generasi muda yang aktif dalam pelestarian tradisi ini menunjukkan kebanggaan mereka terhadap warisan budaya ini. “Kami bangga dengan tradisi ini. Ini bukan hanya tentang kepercayaan, tetapi juga tentang menjaga warisan budaya dan kearifan lokal,” ujar Kak Sarah.
Kenduri tolak bala di Desa Pantai Balai adalah lebih dari sekadar ritual. Ia adalah identitas kultural yang menyatukan masyarakat dan berpotensi menjadi daya tarik wisata budaya. Di tengah derasnya arus globalisasi, tradisi ini menunjukkan bahwa kearifan lokal masih memiliki tempat yang penting dalam hati masyarakat pesisir Aceh.
Penulis: Fazzahra Dwi Cia