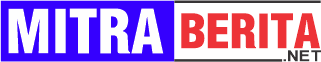MITRABERITA.NET | Seratusan tenaga medis yang terdiri dari dokter spesialis, dokter umum, perawat, hingga bidan di tiga rumah sakit milik Pemerintah Aceh: RSUD Zainoel Abidin (RSUDZA), RS Jiwa Aceh, dan RS Ibu dan Anak (RSIA), dipaksa memilih dua pilihan, jasa medis atau TPP.
Masalah ini bermula dari penerapan Peraturan Gubernur Aceh No. 15 Tahun 2024 dan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 800.1.5/715/2024, yang mengatur tentang Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi ASN.
Dalam praktiknya, kebijakan itu justru menimbulkan polemik karena memaksa rumah sakit memilih antara TPP atau jasa medis, padahal keduanya memiliki dasar hukum dan sumber dana berbeda.
Para tenaga medis menilai kebijakan ini mendiskriminatif dan tidak berdasar, serta mencerminkan lemahnya pemahaman pemerintah terhadap sistem pelayanan kesehatan yang kompleks dan berisiko tinggi.
“Beban kerja dokter dan perawat tidak bisa disamakan dengan pegawai administrasi. Kami berhadapan dengan nyawa manusia setiap hari, tapi justru diperlakukan seolah hanya angka di tabel birokrasi,” ujar salah satu dokter spesialis yang ikut dalam aksi demo di Kantor Gubernur Aceh, Selasa 11 November 2025.
Ironisnya, menurut penuturan para tenaga medis itu, peraturan tersebut disahkan tanpa melibatkan manajemen rumah sakit maupun organisasi profesi medis. Menurut sejumlah sumber di lingkungan rumah sakit, proses penyusunan Pergub berlangsung tertutup dan tanpa uji publik.
Padahal, UU Kesehatan No. 17 Tahun 2023 dan Permenkes No. 28 Tahun 2014 dengan tegas menyebut bahwa jasa medis adalah hak tenaga kesehatan yang bersumber dari pendapatan rumah sakit, termasuk dari klaim BPJS Kesehatan.
Namun, sejak April 2024, pembayaran jasa medis tertahan di kas rumah sakit. Hal ini terjadi karena Sekretaris Daerah Aceh M Nasir menginstruksikan agar rumah sakit hanya memilih satu skema: TPP atau jasa medis.
“Kami tetap bekerja siang malam, tapi hak kami tidak kunjung dibayar. Jasa medis bukan bonus, itu hak profesional atas tanggung jawab yang besar,” kata seorang perawat RS Jiwa Aceh saat menjelaskan kepada wartawan.
Upaya klarifikasi sempat dilakukan oleh RSUDZA dengan menghadirkan Tim TPP dan BLUD dari Kemendagri pada Oktober 2025 lalu. Hasilnya sang jelas, tidak ada aturan nasional yang melarang pemberian TPP dan jasa medis secara bersamaan.
Artinya, kebijakan Pemerintah Aceh era Penjabat Gubernur Aceh Bustami Hamzah itu tidak hanya kontraproduktif, tetapi juga berpotensi melanggar regulasi di atasnya.
Anehnya, menurut informasi yang diterima media ini, hanya tiga rumah sakit di Aceh yang menerapkan sistem “wajib pilih” itu. Provinsi lain di Indonesia tetap memberikan TPP sekaligus jasa medis tanpa masalah.
Aceh, disebut sebagai satu-satunya daerah yang memaksa tenaga medis memilih antara hak dan tanggung jawab. Hal tersebut dianggap sebagai bentuk ketidakadilan terhadap tenaga medis, yang tak bisa ditoleransi.
Pada September dan Oktober 2025, perwakilan tenaga medis dari RS Jiwa dan RSIA telah dua kali menemui Sekda Aceh untuk meminta revisi kebijakan. Namun hingga November, janji revisi itu tak pernah terwujud.
Sementara itu, moral tenaga kesehatan di rumah sakit provinsi kian merosot. Banyak dari mereka mengaku merasa diperlakukan hanya sebagai pelengkap sistem birokrasi, bukan sebagai tenaga profesional dengan tanggung jawab besar terhadap keselamatan pasien.
“Kami tetap berjuang demi kemanusiaan. Tapi ketika hak kami diabaikan, profesi ini terasa tidak dihargai. Jasa medis bukan soal uang, tapi soal martabat,” tutur seorang dokter RSIA dengan nada getir.
Fenomena ini menjadi cermin buram wajah birokrasi Aceh. Ketika tenaga medis yang menjadi garda terdepan dalam menjaga kesehatan masyarakat, justru diperlakukan seperti mesin administrasi, yang terancam bukan hanya kesejahteraan mereka, tetapi juga kualitas pelayanan publik.
Penulis: Hidayat Pulo | Editor: Redaksi