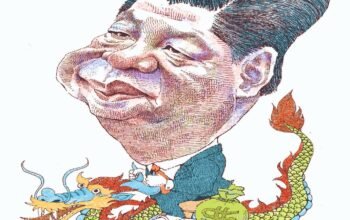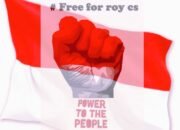KETIKA Presiden Prabowo Subianto tengah menyiapkan pembentukan Tim Reformasi Polri sebagai jawaban atas desakan publik yang kian menguat, publik justru dikejutkan oleh keluarnya Surat Perintah Kapolri Nomor Sprin/2749/IX/TUK.2.1./2025 pada 17 September 2025. Surat ini menetapkan pembentukan “Tim Transformasi Reformasi Polri” yang terdiri dari 52 personel internal Polri. Pengumuman itu dilakukan tepat ketika Presiden berada di luar negeri, seolah mengirimkan pesan bahwa Polri memiliki jalannya sendiri dalam mendefinisikan agenda reformasi.
Dalam studi tata kelola negara modern, kondisi ini bisa dibaca melalui teori principal agent. Presiden adalah principal yang memegang mandat politik rakyat, sementara Polri adalah agent yang seharusnya tunduk pada garis kebijakan politik tersebut. Namun, saat agent melangkahi principal, yang terjadi adalah agency problem, dimana potensi pembangkangan dan usaha mempertahankan otonomi kekuasaan di luar kendali sipil. Manuver Kapolri dengan sendirinya menimbulkan pertanyaan serius, apakah Polri sedang berbenah atau justru mempertahankan posisi dominannya dalam piramida kekuasaan negara?
Reformasi Polri bukan sekadar urusan administratif, melainkan persoalan politik dalam arti substantif yakni siapa yang berkuasa atas aparat keamanan, dan bagaimana akuntabilitasnya dijaga. Sejarah Reformasi 1998 jelas menuntut agar supremasi sipil ditegakkan, bukan dilemahkan. Namun, langkah Kapolri membentuk timnya sendiri, tanpa koordinasi dengan Presiden, justru mengirimkan sinyal resistensi terhadap reposisi Polri dalam kerangka demokrasi.
Pelajaran dari era Presiden Jokowi masih segar, meski anggaran Polri terus meningkat, legitimasi publik justru merosot. Survei Indikator Politik Indonesia pada awal 2024 menunjukkan kepercayaan publik terhadap Polri turun di bawah 60 persen, terendah sejak Reformasi. Skandal besar, mulai dari kasus Ferdy Sambo hingga praktik mafia di sektor tambang dan migas, memperkuat citra Polri yang melenceng dari mandat konstitusionalnya. Padahal, dalam APBN 2024, Polri memperoleh alokasi lebih dari Rp104 triliun, menjadikannya salah satu institusi sipil dengan anggaran terbesar di republik ini. Ironisnya, dengan sumber daya sebesar itu, crime clearance rate stagnan di kisaran 50-55 persen, sementara laporan tentang pungli, kekerasan aparat, dan penyalahgunaan wewenang terus bermunculan.
Kontradiksi ini menegaskan bahwa problem Polri bukan pada kekurangan sumber daya, melainkan pada desain institusi, kultur kekuasaan, dan lemahnya akuntabilitas. Jika reformasi dibatasi hanya pada ruang internal, apalagi dikendalikan langsung oleh Kapolri, hasilnya hanya akan berupa kosmetika birokrasi, bukan transformasi sejati. Seperti diingatkan Karl Popper, institusi hanya akan sebaik mekanisme pengawasan yang mengendalikannya. Karena itu, reformasi Polri harus inklusif, melibatkan masyarakat sipil, akademisi, dan praktisi hukum independen, bukan hanya 52 personel internal.
Secara konstitusional, mandat Polri jelas dalam Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 menyebut Polri bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, melindungi, mengayomi, melayani, serta menegakkan hukum. Namun, UU No. 2/2002 tentang Polri justru menambahkan istilah “keamanan dalam negeri” yang berkelindan dengan narasi “keamanan nasional”. Distorsi inilah yang membuka ruang deviasi fungsi Polri, dari aparat sipil menjadi kekuatan quasi-militer yang kerap masuk ke ranah politik.
Belajar dari pengalaman negara lain, model kepolisian yang sehat selalu berdiri di atas kerangka akuntabilitas sipil. Inggris menempatkan kepolisian di bawah Home Office, Jerman membaginya dalam struktur federatif di bawah Bundesministerium des Innern, sementara Jepang membentuk National Public Safety Commission yang diawaki unsur sipil independen. Semua desain itu menegaskan hal yang sama bahwa polisi harus kuat, tetapi tetap terkendali dalam kerangka sipil.
Indonesia tidak bisa terus menunda pembenahan. Reformasi Polri harus menyentuh empat aspek mendasar yaitu sistem, kewenangan, struktur, dan kultur. Sistem harus transparan dan akuntabel, kewenangan harus dikembalikan sesuai amanat konstitusi, struktur perlu ditata ulang agar tidak menjadikan Polri superbody, dan kultur harus digeser dari gaya militeristik menuju pelayanan sipil. Tanpa itu, Polri hanya akan terus menjadi institusi yang mampu mengerjakan semua hal, kecuali tugas utamanya yaitu menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
Pertaruhan kali ini jelas, apakah Presiden akan membiarkan Kapolri mendikte arah reformasi, ataukah supremasi sipil benar-benar ditegakkan? Jika Presiden lengah, maka publik hanya akan menyaksikan repetisi kegagalan, dimana reformasi yang berakhir sebagai slogan, sementara institusi Polri semakin sulit disentuh.
Supremasi sipil tidak boleh sekadar menjadi jargon konstitusional. Ia harus diwujudkan dalam tindakan nyata. Reformasi Polri adalah ujian pertama Presiden Prabowo, apakah ia berani menempatkan kepolisian kembali pada rel demokrasi, atau membiarkan Polri terus menjadi kekuatan otonom yang menantang kendali sipil.
Ditulis oleh: Sri Radjasa, M.BA (Pemerhati Intelijen)