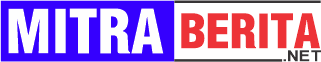DITENGAH derasnya arus moralitas yang terus dipertanyakan, selalu ada sosok yang memilih jalan tikus: licik, culas, dan lihai mengelabui. Kisah yang terjadi di sebuah SMA di Aceh menjadi potret nyata dari perangai ini. Sang kepala sekolah, yang seharusnya menjadi teladan integritas, justru tampil sebagai aktor utama dalam drama memalukan bernama pungutan liar. Dengan dalih “biaya ijazah,” ia meminta Rp50 ribu dari siswa yang ingin mengambil hak mereka—ijazah yang seharusnya diberikan tanpa embel-embel pungutan apapun.
Ketika pemberitaan mencuat, alih-alih merenung dan bertanggung jawab, kepala sekolah ini justru memainkan peran korban. Dengan penuh drama, ia menyalahkan siswa, warga, bahkan wartawan yang berani membuka boroknya. Seolah dunia bersalah kepadanya, ia mengumpulkan dukungan dari orang tua siswa, tokoh masyarakat dan tokoh adat, memanfaatkan posisi mereka untuk menutupi kesalahannya.
Ironisnya, orang tua siswa, tokoh masyarakat dan tokoh adat yang diundang untuk membela justru tidak menyaksikan peristiwa tersebut. Mereka dijadikan alat pembenaran dengan cara yang licik. Lebih parah lagi, tindakan kepala sekolah yang merobek fotokopi ijazah di depan siswa dan seorang warga adalah simbol dari arogansi kekuasaan kecil yang ia genggam. Ia seperti tikus yang ketahuan mencuri, tapi pura-pura lemas di depan kucing agar dianggap tak bersalah.
Namun, tikus tetaplah tikus. Dalam budaya kita, tikus kerap diidentikkan dengan pencuri dan koruptor. Sifat mereka yang suka mencuri diam-diam tidak hanya merusak barang, tetapi juga merusak kepercayaan. Begitu pula dengan tindakan pungli—meskipun jumlahnya kecil, dampaknya besar. Ia mengikis rasa keadilan, menanamkan ketidakpercayaan, dan mempermalukan institusi yang seharusnya menjadi pilar moral.
Lebih miris, tokoh adat yang seharusnya menjadi penjaga nilai justru ikut terjebak dalam permainan licik ini. Dengan membuat pernyataan membela kepala sekolah tanpa memahami persoalan sebenarnya, ia merendahkan etika dan martabatnya sendiri. Pernyataan yang dibuat itu bahkan berpotensi menjadi pembohongan publik. Dan apakah kepala sekolah peduli? Tentu saja tidak. Ia hanya ingin aman, tanpa peduli siapa yang dikorbankan dalam prosesnya.
Sosok kepala sekolah ini menjadi cerminan bahwa berbicara bijak bukanlah bukti kebijaksanaan. Kebijaksanaan sejati terletak pada tindakan, bukan kata-kata. Tugas seorang pemimpin, baik kecil maupun besar, adalah menjaga integritas, bukan merusaknya. Merobek fotokopi ijazah, menyalahkan pihak lain, hingga memanfaatkan orang-orang tak bersalah demi kepentingan pribadi adalah tindakan yang jauh dari tanggung jawab seorang pemimpin.
Kisah ini bukan sekadar sindiran, tapi pengingat pahit tentang bagaimana integritas sering kali menjadi korban. Kita butuh lebih banyak orang yang berani berbicara, bertindak, dan membela kebenaran, bukan tikus-tikus licik yang gemar berlindung di balik topeng moralitas palsu. Karena tikus yang dibiarkan berkeliaran akan terus merusak, mencuri, dan melarikan diri dari tanggung jawab.
Jangan biarkan perangai tikus mendominasi. Kebenaran harus terus digemakan, sampai akhirnya mereka yang bermain di jalan gelap dipaksa keluar dari persembunyiannya. Atau, jika perlu, kita siapkan perangkap agar mereka tak lagi leluasa mencuri hak orang lain.