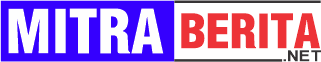FAJAR di Gaza tidak lagi membawa harapan. Ia datang hanya untuk mengungkapkan pemandangan yang sama setiap hari: puing-puing, darah yang mengering di aspal, dan jeritan yang tertahan di tenggorokan.
Bau mesiu bercampur debu bangunan yang runtuh memenuhi udara, menyesakkan paru-paru siapa pun yang mencoba bernapas.
Di sebuah gang sempit, Ahmed Hirz duduk memeluk anaknya. Lelaki itu sudah delapan kali mengungsi sejak Israel melancarkan operasi darat pada Oktober 2023.
“Lebih baik mati di sini,” ucapnya lirih, seperti dikutip media Al Jazeera, Sabtu 9 Agustus 2025.
Matanya tidak menatap reporter yang mewawancarainya, melainkan lurus ke arah reruntuhan rumah yang pernah ia tinggali. Ia tahu, jika pergi ke selatan pun, maut akan tetap menunggu di tikungan jalan.
Di sisi lain kota, Rajab Khader menolak meninggalkan rumahnya. Seekor kucing kurus melingkar di pangkuannya.
“Israel tidak akan menemukan apa pun kecuali jasad dan nyawa kita,” katanya tegas.
Kalimat itu bukan heroisme kosong, melainkan keputusasaan yang sudah menjadi tekad.
Maghzouza Saada, perempuan dari Beit Hanoon, berdiri di tengah jalan, memandang kosong ke arah barat.
“Selatan tidak aman. Kota Gaza tidak aman, utara tidak aman. Ke mana kita harus pergi? Apakah kami harus menceburkan diri ke laut?” suaranya pecah, setengah teriak, setengah menangis.
Di hotel-hotel mewah ribuan kilometer dari Gaza, para pemimpin dunia Islam berkumpul.
Mereka berfoto, bersalaman, dan mengeluarkan pernyataan keras yang berakhir di meja pers. Setelah itu, semua pulang ke istana masing-masing.
Tak ada satu pun tank atau pasukan yang bergerak, tak ada satu pun embargo ekonomi yang dijatuhkan, tak ada keberanian untuk benar-benar menghentikan Zionis.
Umat Islam katanya satu tubuh. Jika satu bagian sakit, seluruh tubuh ikut merasakan. Tapi Gaza telah berdarah puluhan tahun, dan tubuh besar itu hanya merasakan gatal yang diobati dengan kata-kata manis.
Mereka lupa, darah yang mengalir di Gaza adalah darah saudara sendiri.
Sementara itu, Barat yang selalu mengaku sebagai pembela demokrasi dan HAM, memperlihatkan tak malu-malu memperlihatkan wajah asli mereka yang munafik.
Mereka cepat marah jika satu gedung di negara sekutunya terkena serangan. Tapi ketika ratusan rudal menghantam rumah sakit di Gaza, mereka mengirim senjata tambahan untuk Israel.
Mereka tidak buta. Mereka melihat anak-anak mati kelaparan. Mereka tidak tuli. Mereka mendengar jeritan ibu-ibu yang kehilangan keluarga. Tapi mereka memilih menutup mata, menutup telinga, dan menutup hati.
Di setiap sudut Gaza, orang-orang telah mengemasi barang seadanya. Bukan karena tahu akan pergi ke mana, tapi karena mereka tahu tentara Israel akan datang kapan saja untuk memaksa mereka keluar.
Mereka siap, tapi bukan untuk menyerah. Mereka siap untuk mati di tanah mereka sendiri.
Rumah sakit kini menjadi kuburan. Tidak ada listrik, tidak ada obat, dan tidak ada air bersih.
Lansia terbaring di ranjang tanpa perawatan, pasien luka parah dibiarkan menunggu maut.
Banyak yang mati bukan hanya karena peluru atau bom, tapi juga karena perut kosong selama berbulan-bulan.
Gaza adalah cermin yang memantulkan wajah asli dunia. Wajah dunia Islam yang lemah dan sibuk berpidato. Wajah Barat yang munafik dan berdarah dingin. Wajah umat manusia yang sudah mati rasa.
Sejarah akan mencatat bahwa ketika Gaza hancur, bukan hanya rakyat Palestina yang terbunuh, tapi juga nurani dunia.
Dan itu akan menjadi aib yang tak bisa dibasuh oleh waktu, doa, atau resolusi PBB sekalipun.
Hari ini, Gaza adalah kuburan terbuka. Dan kita semua hanya bisa diam, marah pada diri sendiri, lambat dan pura-pura peduli, sementara warga Palestina setiap harinya hanya merasakan penderitaan.
Pemimpin Islam? Setiap saat terus menimbun harta dengan berbagai cara termasuk korupsi uang negara.
Di sisi lain, setiap saat mereka berupaya mempertahankan tahta dan menganggap tidak akan pernah meninggalkan dunia. Hidup memang harus kaya, tapi jangan sampai nurani menjadi buta!