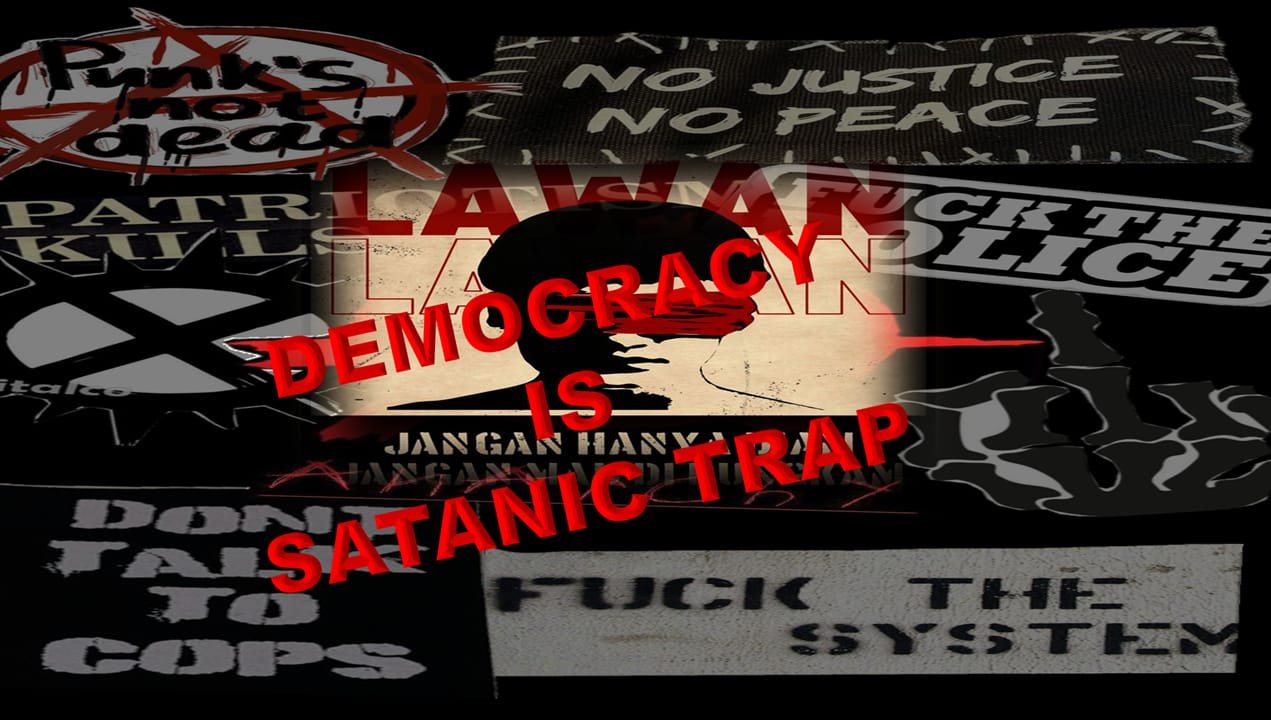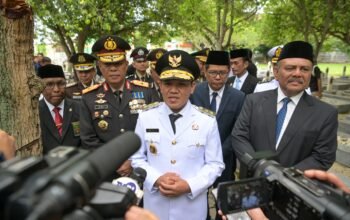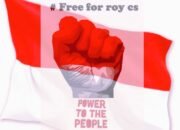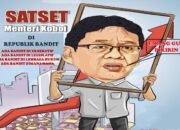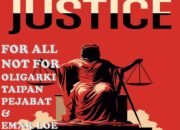KERUSUHAN di Nepal dan Indonesia pada tahun 2025 bukan sekadar gejolak politik biasa, tapi menyingkap krisis legitimasi dan kepercayaan pada demokrasi dari generasi muda, terutama Gen Z. Data ekonomi dan survei menunjukkan bahwa kerusuhan ini bukan hawa panas sesaat, melainkan akumulasi kegagalan sistem yang mulai “mematikan” demokrasi, bukan lewat kudeta, tetapi lewat keputusasaan kolektif.
Di Nepal, gelombang protes Gen Z yang paling mematikan sejak beberapa dekade terakhir telah menelan korban jiwa puluhan orang dan ribuan luka-luka. Sektor pariwisata yang menyumbang sekitar 8% dari PDB Nepal juga mengalami pukulan telak, dimana angka kunjungan turis turun 30% dibanding tahun sebelumnya.
Hotel-hotel mewah tak luput dari kerusakan, dimana Industri perhotelan diperkirakan kehilangan 25 miliar rupee Nepal (US$190 juta) karena vandalisme, pembakaran, dan pengrusakan. Lebih dari 10.000 orang kehilangan pekerjaan secara mendadak akibat kerusakan di hotel, restoran, dan sektor retail di kota-kota besar.
Sementara di Indonesia, kerusuhan yang dipicu oleh isu tunjangan besar anggota parlemen dan ketidaksetaraan makin menyulut kemarahan publik. Contohnya, unjuk rasa di Jakarta dari tanggal 25 sampai 29 Agustus 2025 menyebabkan kerusakan infrastruktur publik senilai Rp55 miliar atau sekitar US$3,2–3,6 juta, termasuk fasilitas MRT, halte TransJakarta, dan kamera pengawas yang dirusak. Di sisi lain, estimasi kerusakan properti di seluruh Indonesia akibat kerusuhan mencapai Rp900 miliar atau setara US$55 juta.
Secara institusional, survei memperlihatkan bahwa publik di Indonesia masih memiliki kepercayaan tinggi terhadap beberapa lembaga, tetapi kepercayaan ini tidak merata dan mulai terkikis ketika menyangkut partai politik, legislatif, dan elite yang dianggap korup.
Sebagai contoh, survei oleh Indonesia Political Opinion (IPO) Mei 2025 menunjukkan bahwa presiden dan militer (TNI) memiliki tingkat kepercayaan yang sangat tinggi yakni 97,5% untuk presiden, dan 92,8% untuk militer, sementara institusi legislatif dan partai politik tidak mendapat sorotan kepercayaan sebesar itu.
Apa makna semua ini dalam konteks “pembunuhan demokrasi”? Pertama, angka kerusakan ekonomi sangat besar, baik di Nepal maupun Indonesia, tidak hanya sebagai efek samping demonstrasi, tetapi sebagai cermin bahwa rakyat terutama Gen Z mulai menghitung bahwa “biaya diam” terlalu mahal.
Kedua, kepercayaan pada institusi formal yang seharusnya menjadi perantara demokrasi baik legislatif, eksekutif yang bersih, keadilan tampaknya runtuh di mata generasi muda, bila institusi tak mampu mewujudkan keadilan dan kesejahteraan, maka legitimasi mereka pun dipertanyakan.
Ketiga, pola tanpa pemimpin tunggal, bergerak melalui jejaring sosial, munculnya provokator, serta aksi yang cepat meluas. Semua ini memperlihatkan bahwa Gen Z tidak lagi menunggu kanal politik tradisional. Mereka melihat bahwa kanal tersebut telah dibajak oleh elite yang menempatkan keuntungan pribadi dan kekuasaan di atas kepentingan umum. Sekaligus, mereka memandang bahwa demokrasi prosedural yaitu pemilu, slogan kebebasan, keterbukaan yang telah kehilangan substansi jika tidak disertai akuntabilitas dan rasa keadilan yang nyata.
Sedangkan filosofi politik klasik seperti Rousseau tentang kontrak sosial dan Plato tentang bahaya demokrasi yang tidak stabil kembali relevan. Bila kontrak sosial dilanggar terus menerus, bila demokrasi hanya jadi fasad, maka reaksi rakyat terutama generasi yang paling mendengar ini janji bukan reformasi biasa, melainkan semacam ruptur yang revolusi emosional dan eksistensial.
Untuk mencegah “kematian demokrasi karena keputusasaan”, elite politik harus bergerak cepat dengan bukti konkret berupa pengurangan tunjangan yang berlebihan, transparansi publik anggaran dan aset milik elit, tindakan nyata atas kekerasan aparat, perlindungan hukum yang adil, dan mekanisme kompensasi atas kerusakan ekonomi yang ditimbulkan oleh kerusuhan, bukan sekadar janji.
Ditulis oleh: Sri Radjasa, M.BA (Pemerhati Intelijen)