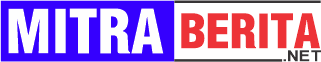SALAH satu tolok ukur kemajuan sebuah peradaban adalah cara ia memandang dan memperlakukan perempuan. Dalam lintasan sejarah manusia, tidak sedikit masyarakat yang membangun kemegahannya di atas penindasan terhadap kaum perempuan, menjadikan mereka sebagai objek, pelengkap, bahkan beban sosial. Dalam konteks inilah, kehadiran Nabi Muhammad SAW menandai sebuah revolusi moral dan kemanusiaan yang luar biasa, yaitu mengangkat derajat perempuan dari ketertindasan menuju kemuliaan.
Sebelum Islam datang, masyarakat Arab jahiliyah hidup dalam sistem nilai yang keras dan maskulin. Perempuan dipandang rendah, tidak memiliki hak, dan sering kali menjadi korban kekerasan struktural. Praktik mengubur bayi perempuan hidup-hidup merupakan simbol paling kejam dari pandangan ini.
Seorang ayah bisa merasa malu dan terhina hanya karena dianugerahi anak perempuan. Dalam situasi seperti ini, Islam hadir sebagai cahaya pembebasan yang menegaskan bahwa perempuan adalah manusia seutuhnya, bukan aib, bukan beban, dan bukan milik siapa pun.
Al-Qur’an dengan tegas mengecam praktik pembunuhan bayi perempuan dan mengembalikan hak hidup serta kehormatan mereka. Namun misi Nabi Muhammad SAW tidak berhenti pada penghapusan praktik kejam tersebut. Lebih dari itu, beliau membangun fondasi etika baru yang menempatkan perempuan sebagai subjek bermartabat dalam kehidupan sosial, hukum, dan spiritual. Perempuan tidak lagi diposisikan sebagai objek kepemilikan, melainkan sebagai individu yang memiliki kehendak, hak, dan tanggung jawab.
Salah satu terobosan besar Islam adalah pemberian hak waris kepada perempuan. Dalam masyarakat Arab pra-Islam, harta warisan hanya menjadi hak laki-laki. Islam datang membawa perubahan radikal dengan menetapkan bahwa perempuan juga berhak atas warisan, sekalipun dengan porsi yang diatur secara proporsional berdasarkan tanggung jawab sosial. Hak ini bukan sekadar persoalan ekonomi, tetapi pengakuan atas eksistensi dan kemandirian perempuan sebagai subjek hukum.
Lebih jauh, Islam memberikan perempuan hak kepemilikan penuh atas harta mereka. Seorang perempuan berhak mengelola, menggunakan, dan mengembangkan hartanya tanpa harus kehilangan identitas atau kebebasan. Bahkan dalam ikatan pernikahan, Islam membuka ruang keadilan melalui hak khulu’, yaitu hak perempuan untuk mengakhiri pernikahan jika tidak lagi menemukan kebahagiaan dan keadilan. Ini menunjukkan bahwa pernikahan dalam Islam bukanlah penjara, melainkan ikatan etis yang harus dijaga oleh kedua belah pihak.
Dalam dimensi keluarga, Nabi Muhammad SAW memuliakan perempuan melalui pengangkatan derajat ibu ke posisi yang sangat tinggi. Sabda beliau yang menyatakan bahwa “Surga berada di bawah telapak kaki ibu” bukan sekadar ungkapan spiritual, tetapi pesan filosofis yang mendalam. Islam menempatkan ibu sebagai pusat pendidikan dan pembentukan karakter manusia. Dari rahim, pelukan, dan kasih sayang seorang ibu, lahir generasi yang akan menentukan arah peradaban.
Konsep ini menegaskan bahwa peradaban besar tidak dibangun oleh kekuatan senjata semata, tetapi oleh nilai-nilai yang ditanamkan sejak dini. Ibu dalam Islam adalah madrasah pertama, tempat anak belajar tentang cinta, moralitas, dan kemanusiaan. Dengan memuliakan ibu, Nabi Muhammad SAW sejatinya sedang membangun fondasi peradaban yang berkeadilan dan beradab.
Dalam relasi suami-istri, Nabi Muhammad SAW juga melakukan koreksi besar terhadap budaya patriarki yang menormalisasi kekerasan. Beliau bersabda, “Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istrinya.” Pernyataan ini mengandung pesan etis yang kuat: kualitas iman dan kesalehan seseorang tercermin dari cara ia memperlakukan perempuan, terutama istrinya. Kekerasan, dominasi, dan penghinaan tidak pernah menjadi bagian dari ajaran Islam yang dibawa Nabi.
Lebih menarik lagi, Nabi Muhammad SAW tidak menutup ruang publik bagi perempuan. Sejarah Islam mencatat kehadiran perempuan dalam berbagai bidang, termasuk pendidikan, ekonomi, bahkan perjuangan fisik. Sosok Nussaibah binti Ka‘ab menjadi contoh nyata bagaimana perempuan memiliki peran aktif dan mulia dalam membela kebenaran. Keberaniannya di medan perang diapresiasi langsung oleh Rasulullah, menegaskan bahwa perempuan bukan makhluk pinggiran dalam sejarah Islam.
Pada level teologis, Islam menegaskan prinsip kesetaraan spiritual antara laki-laki dan perempuan. Keduanya diciptakan dari satu jiwa yang sama dan memiliki kedudukan setara di hadapan Allah. Perbedaan biologis tidak pernah dijadikan alasan untuk ketidakadilan atau penindasan. Dalam pandangan Islam, ukuran kemuliaan manusia bukanlah jenis kelamin, melainkan ketakwaan dan akhlak.
Sayangnya, dalam praktik sosial kontemporer, nilai-nilai luhur ini sering kali tereduksi oleh budaya, tradisi, atau tafsir sempit yang tidak sejalan dengan spirit ajaran Nabi. Ketidakadilan terhadap perempuan yang masih terjadi di berbagai tempat sering kali lebih merupakan warisan budaya patriarki daripada ajaran Islam itu sendiri. Di sinilah pentingnya kembali membaca sejarah dan misi Nabi Muhammad SAW secara jujur dan kritis.
Nabi Muhammad SAW datang bukan hanya membawa ritual keagamaan, tetapi visi besar tentang keadilan, kasih sayang, dan kemanusiaan. Pengangkatan derajat perempuan merupakan bagian integral dari misi tersebut. Memuliakan perempuan berarti memuliakan kehidupan, keluarga, dan masa depan peradaban.
Karena itu, tugas umat Islam hari ini bukan sekadar mengagungkan sejarah, tetapi mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan nyata. Ketika perempuan dimuliakan, diberi ruang, dan diperlakukan dengan adil, maka masyarakat akan tumbuh lebih manusiawi. Dan itulah warisan terbesar Nabi Muhammad SAW: membangun peradaban yang berdiri di atas keadilan dan kasih sayang bagi seluruh manusia.
Namun, penting ditegaskan bahwa perjuangan memuliakan perempuan tidak boleh terjebak pada narasi sepihak yang hanya menuntut penghargaan tanpa diiringi kesadaran akan kewajiban dan etika relasi. Fenomena hari ini menunjukkan sebagian perempuan kerap merasa tidak dihargai, tidak dimuliakan, dan selalu berada pada posisi korban, namun pada saat yang sama juga abai dalam menghargai peran dan kepemimpinan suami.
Sikap merendahkan, membangkang, bahkan menolak dialog yang beradab sering kali justru memperlebar jurang ketidakharmonisan rumah tangga. Dalam konteks poligami, misalnya, penolakan keras sering kali dilakukan bukan melalui pendekatan etis dan musyawarah, melainkan dengan kemarahan, penghakiman, dan pengingkaran total, seolah-olah seluruh ajaran Islam harus tunduk pada perasaan semata. Padahal Islam tidak pernah mengajarkan relasi kuasa sepihak, baik oleh laki-laki maupun perempuan, melainkan keseimbangan antara hak dan kewajiban, antara penghormatan dan ketaatan yang berlandaskan akhlak.
Mengaku terzalimi tetapi terus-menerus melukai martabat pasangan bukanlah cerminan nilai yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Sebab kemuliaan perempuan dalam Islam bukan hanya terletak pada hak yang dituntut, melainkan juga pada kebijaksanaan, adab, dan kemampuan menjaga keharmonisan dengan sikap saling menghargai dalam bingkai syariat dan keadilan.
Ditulis oleh: Hidayat. S., S.Fil.I (Sarjana Filsafat Islam)