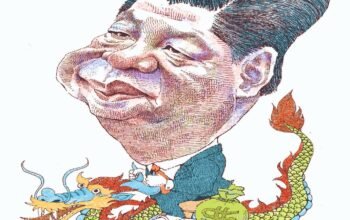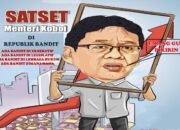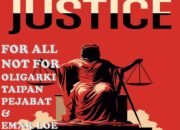KASUS tuduhan ijazah palsu terhadap Joko Widodo yang berujung pada penetapan delapan orang sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya termasuk figur publik Roy Suryo adalah lebih dari sekadar sengketa hukum antarpihak. Ia adalah gejala yang membacakan ulang luka lama nasional, terkait relasi retak antara kekuasaan, hukum, dan cita-cita kebangsaan.
Pada 7-8 November 2025, Polda Metro Jaya mengumumkan delapan tersangka dan penyitaan 723 item barang bukti, sekaligus menyebut pemeriksaan ratusan saksi dan sejumlah ahli dalam proses gelar perkara. Fakta-fakta ini menandai bahwa perkara tersebut bukan remeh, namun pembacaan publik terhadap maknanya jauh lebih penting daripada daftar barang bukti itu sendiri.
Pertama, kita harus membedakan antara fakta forensik dan politik hukum. Puslabfor Polri disebut melakukan analisis analog dan digital yang menjadi salah satu dasar penyidikannya; penyimpulan teknis semacam ini lazim dalam perkara dokumen. Tetapi ketika penegakan hukum tampak dipetakan ke arah yang lebih cepat menjerat pengkritik dibanding menelusuri klaim terhadap kekuasaan, muncul pertanyaan mendasar: apakah hukum dilaksanakan sebagai mesin pencari kebenaran atau sebagai janitor politik yang membersihkan citra penguasa?
Tempo dan media lain melaporkan bahwa penyidik mengklaim adanya edit dan manipulasi dokumen sebagai temuan, publik berhak menuntut keterbukaan metodologis atas klaim semacam ini agar prosesnya tidak menjadi tertutup dan menimbulkan kecurigaan. Kedua, konteks normatif berubah dan itu penting. KUHP baru membuka babak baru dalam relasi kebebasan berpendapat dan delik penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden.
Kritikus KUHP sejak lama memperingatkan potensi “pasal karet” yang dapat digunakan untuk membungkam kritik, dan kajian akademik bersama analisis hukum memperlihatkan risiko pengembalian praktik kriminalisasi terhadap wacana politik. Dalam konteks itu, ketika seseorang menyelediki dokumen pejabat publik lalu berhadapan dengan ancaman pidana yang lebih berat, tekanan terhadap ruang publik demokratis menjadi nyata. Koridor hukum yang semula dimaksudkan untuk menjaga kehormatan negara bisa berubah menjadi alat intimidasi.
Ketiga, masalah legitimasi institusi penegak hukum tidak dapat disepelekan. Survei publik tentang kinerja penegak hukum menunjukkan gambaran yang campur aduk, yaitu ada hasil survei yang menunjukkan peningkatan kepuasan publik terhadap Polri dalam beberapa indikator, sementara survei lain menunjukkan tingkat kepercayaan yang belum konsisten dan masih rentan kritik publik.
Dalam situasi demikian, setiap tindakan penegakan yang dipandang pilih-kasih akan mengikis modal sosial yang sulit dibangun kembali. Kepercayaan bukan sekadar angka; ia adalah bahan bakar legitimasi demokrasi. Tanpa itu, hukum bukan lagi benteng masyarakat melainkan topeng kekuasaan.
Untuk menyusun analisis yang lebih filosofis, kita harus kembali ke gagasan Pancasila sebagai basis moral kenegaraan. Pancasila menegaskan kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan, kerakyatan yang dipimpin hikmat kebijaksanaan, dan keadilan sosial yakni nilai-nilai yang menuntut penegakan hukum yang adil, terbuka, dan melindungi hak warga untuk mengkritik.
Bung Karno sendiri mengingatkan bahwa nasionalisme sejati bukan pengagungan penguasa, melainkan cinta pada bangsa yang menghendaki keadilan dan martabat bersama. Ketika hukum tampak menjadi instrumen untuk menutup kritik terhadap figur publik, ia bertentangan dengan semangat Pancasila dan gagasan nasionalisme yang inklusif. Negara yang berdaulat menurut filsafat Pancasila harus mampu menampung koreksi, bukan menjeratnya.
Literatur kajian hukum memperkaya titik pandang ini. Para akademisi telah menulis tentang bagaimana undang-undang pidana yang terlalu mudah menjerat ekspresi akan menimbulkan chilling effect: warga takut berbicara, pers kehilangan fungsi kontrol, dan ruang perdebatan publik menyempit.
Studi tentang transisi demokrasi menegaskan bahwa kinerja lembaga penegak hukum adalah penentu utama apakah demokratisasi berlanjut ke kedewasaan atau kembali terjerumus ke pola otoritarianisme terselubung. Praktik yang menempatkan hukum pada sisi kekuasaan merusak jaringan checks and balance yang menjadi inti negara hukum.
Apa implikasinya bagi kebangsaan? Nasionalisme yang sehat tidak identik dengan ketundukan buta. Ia adalah kesadaran kolektif untuk menjaga hajat hidup bersama yaitu keadilan, kesejahteraan, dan martabat. Bila hukum berfungsi menegakkan keadilan, ia memperkokoh nasionalisme; bila hukum berfungsi melindungi citra kekuasaan, ia merongrong rasa kebangsaan.
Bukankah bangsa besar lahir ketika warganya berani menuntut kebenaran dan penguasa berani menegakkan hukum tanpa pilih kasih? Kutipan-kutipan Bung Karno tentang keberanian rakyat menegakkan nasibnya sendiri adalah panggilan untuk memperkuat kembali roh itu, bukan untuk menghidupkan nostalgia konfrontasi, tetapi untuk membangun tata kelola hukum yang menghormati martabat semua pihak.
Akhirnya, solusi bukan pada semburan retorika, melainkan perbaikan institusional dengan transparansi penuh atas metode penyidikan forensik, pembukaan akses publik terhadap dasar pertimbangan gelar perkara (tanpa merusak proses hukum), penguatan mekanisme pengawasan eksternal terhadap penyidik, dan perlindungan bagi kebebasan sipil yang sah. Debat hukum harus terjadi di ruang publik yang jujur, bukan di koridor intimidasi. Jika negara ingin menjaga martabatnya di mata sejarah, maka hukum harus dibawa kembali ke pangkuan kebenaran dan keadilan, sesuai prinsip-prinsip Pancasila yang menjadi fondasi bangsa.
Kasus ini seharusnya menjadi momen introspeksi, apakah kita akan membiarkan hukum menjadi alat konsolidasi kekuasaan, atau menjadikannya kembali sebagai roh yang menyatukan bangsa? Pilihan itu menentukan apakah kita akan diteruskan sebagai bangsa yang merdeka dan bermartabat, atau menyaksikan kepercayaan publik terkikis hingga bangsa kehilangan cerminnya sendiri.
Ditulis oleh: Sri Radjasa (Pemerhati Intelijen)