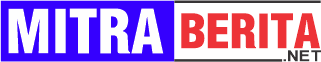“Kami sudah sering didata, tapi sampai sekarang tak pernah dapat apa-apa kecuali BLT dari desa, …..” kata Rudi, lirih.
MITRABERITA.NET | Sebuah gubuk reyot dengan dinding yang terbuat dari papan bekas yang lapuk, atapnya dari daun rumbia tua. Berdiri di antara bentangan tambak yang gersang dan kering.
Rumah itu tak tampak seperti tempat tinggal, lebih menyerupai bangunan yang ditinggalkan. Namun di sanalah Rudi (43), istrinya Nilawati (42), dan keempat anak mereka tinggal.
Keluarga miskin tersebut bertahan di tengah kehidupan yang keras, di Gampong (Desa) Me Merbo, Kecamatan Tanah Pasir, Kabupaten Aceh Utara.
Setiap hari, hidup keluarga ini berputar antara pekerjaan serabutan dan harapan-harapan kecil yang nyaris padam. Rudi bukan pegawai, bukan petani tetap, apalagi pemilik tambak.
Ia hanya seorang buruh serabutan. Ketika tak ada panggilan untuk mengangkat semen atau membangun rumah orang, ia turun ke rawa mencari kepiting.
“Kalau nggak ada panggilan bangunan, saya turun ke tambak cari kepiting. Tapi sekarang makin susah, tergantung air, kepiting pun jarang,” kata Rudi, saat diwawancara beberapa wartawan, pada Jumat 18 April 2025.
Matanya berkaca-kaca saat mengucapkan kalimat itu. Tidak hanya karena sulitnya hidup ditambah beratnya beban ekonomi, tapi juga karena ia merasa benar-benar tak dianggap.
Pada siang hari, panas membakar kulit. Saat malam tiba, hawa dingin merayap tanpa ampun ke sela-sela papan rumah. Tak ada listrik, tak ada air bersih, dan saat hujan datang, rumah itu tak lagi mampu melindungi.
“Bila hujan, kami sekeluarga berlindung di bawah terpal agar tidak basah, sedihnya bila hujan saat malam, kami juga sering basah kuyup,” ujarnya polos, tanpa nada marah, hanya pasrah.
Nilawati, sang istri, tak kalah tangguh. Di sela-sela mengurus rumah, ia juga turun ke rawa untuk menangkap kepiting. Bukan untuk memperkaya diri, tapi agar anak-anak bisa makan sekali sehari.
“Saya pernah sebulan tidak mendapat kerjaan, terkadang istri juga menggantikan saya menangkap kepiting, itu pun bisa ditangkap dalam sebulan mungkin hanya 15 hari, selebihnya kita harus mikir bagaimana cari uang, nafkah untuk makan,” jelas Rudi.
Ironisnya, rumah itu sudah sepuluh tahun tidak pernah dialiri listrik. Alasan yang didengar, kabel terlalu jauh. Maka setiap malam, satu-satunya cahaya yang mereka punya hanyalah lentera minyak tanah yang redup dan berasap.
Yang lebih menyakitkan, harapan akan bantuan dari pemerintah nyaris nihil. Berkali-kali petugas datang, melihat-lihat, mencatat, lalu pergi. Tapi hasilnya sama, NIHIL!

“Banyak yang datang hanya untuk lihat-lihat saja, alasan mereka tidak memberi kami rumah, karena tidak punya tanah untuk dibantu bangun rumah, ujungnya ya tidak bisa dibantu,” katanya.
Satu-satunya bantuan yang pernah mereka terima hanyalah Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari Gampong. Tak ada program pemberdayaan, tak ada perhatian khusus, apalagi pembangunan rumah yang layak.
“Kami sudah sering didata, tapi sampai sekarang tak pernah dapat apa-apa kecuali BLT dari desa, terlebih lagi listrik. Mungkin karena rumah kami di tengah tambak, jadi terlupakan,” tegas Rudi dengan suara lirih.
Di tengah situasi Aceh yang dikenal dengan alokasi anggaran daerah yang besar, kisah Rudi dan keluarganya mencuat sebagai ironi menyakitkan, ketika anggaran melimpah, tapi kemiskinan tetap hidup dalam diam. Dalam gelap gulita!
Harapan Rudi tak muluk-muluk. Ia hanya ingin punya sebidang tanah dan rumah yang layak. Tempat anak-anaknya bisa tidur tanpa takut hujan, tanpa menggigil karena dinginnya udara malam.
“Saya berharap pemerintah lebih memperhatikan rakyat kecil seperti kami,” katanya, singkat tapi sarat makna.
Kisah ini bukan hanya tentang satu keluarga. Ini adalah salah satu potret dari ribuan warga miskin yang terabaikan, yang hidup dalam diam, jauh dari sorotan.
Mereka tidak menuntut kemewahan, hanya ingin diperlakukan selayaknya warga negara, dengan hak untuk hidup layak. Apalagi, mereka termasuk warga negara yang harusnya diperhatikan oleh negara.