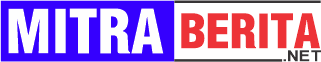MALAM itu, langit Kota Bandroto Ajiancih diselimuti awan gelap yang menutupi sinar bulan. Di tengah gemerlap lampu kota yang memamerkan kemewahan palsu, seorang wanita berdiri kaku di depan Hotel Armeniem Brorrow, salah satu hotel mewah yang katanya memiliki layanan eksklusif untuk “tamu-tamu khusus”.
Namanya Dreaningda. Seorang ibu dua anak yang matanya sembab, wajahnya lelah, dan dadanya sesak oleh kenyataan yang sudah lama ingin ia tolak, tapi akhirnya harus ia telan bulat-bulat malam ini.
Tangannya gemetar memegang kunci kamar yang baru saja ia rebut dari resepsionis, setelah mengancam akan melaporkan skandal besar yang tersembunyi di balik dinding-dinding hotel itu.
Kamar 1306.
Dengan langkah berat, ia menaiki lift. Nafasnya terengah. Setiap detik seperti menampar wajahnya sendiri. Hatinya berharap suaminya tidak ada di sana. Tapi firasatnya lebih tajam dari sekadar harapan. Ia tahu betul bau parfum suaminya yang kini tercium samar dari dalam kamar. Aroma musang betina yang mahal.
Ia membuka pintu dengan suara berderak. Dan di sana, di atas ranjang besar dengan seprei putih yang sudah berantakan, Rambaguttah tertangkap basah sedang memeluk wanita muda yang hanya mengenakan jubah mandi. Lampu kamar redup, tapi cukup terang untuk menyaksikan kehancuran rumah tangga mereka.
“Rambaguttah…” suara Dreaningda pecah, seperti kaca jatuh dari lantai seratus.
Sang suami, yang dikenal masyarakat sebagai tokoh yang baik dan dermawan, penyantun anak yatim, dan wajah utamanya kampanye moral kota, justru terlihat seperti tikus yang baru keluar dari lubang selokan. Pucat, panik, dan penuh rasa bersalah, atau mungkin hanya takut ketahuan.
Wanita di sampingnya langsung lari ke kamar mandi.
“Drean, aku… ini tidak seperti yang kamu pikirkan,” Rambaguttah tergagap, mencoba menyusun kalimat pembelaan.
“Tidak seperti yang aku pikirkan?” Dreaningda tertawa getir.
“Aku sudah tahu berapa banyak hotel yang kau singgahi, berapa banyak wanita yang kau tiduri, dari kota ke kota. Tapi aku masih berharap kau akan berhenti. Aku masih berharap anak-anakmu layak punya ayah. Tapi kau… kau lebih buruk dari bajingan yang tak pernah mengaku beriman.”
Rambaguttah bungkam. Ia tak punya kalimat suci lagi yang bisa dijual malam ini. Topengnya resmi tercabut.
======
Kota Bandroto Ajiancih selalu dipuji sebagai “Kota Keadilan di Bumi Ujung Mars.” Tapi Dreaningda tahu, kota ini seperti lukisan indah yang menutupi dinding berjamur. Segalanya terlihat beres di luar, tapi di dalam, bangkai kejahatan membusuk tak terurus.
Setelah penggerebekan itu, bukannya keadilan yang ia terima, Dreaningda justru dihujat. Masyarakat, yang sebelumnya menganggap Rambaguttah sebagai panutan, malah menuduh Dreaningda pencemburu, tidak sabar, bahkan mengada-ada. Tak ada yang mau mendengarkan kisah luka seorang istri yang ditelantarkan, dicampakkan, dan dihina di hadapan dunia.
Di Kantor Pocolili –kantor yang katanya penegak hukum– laporan Dreaningda tidak pernah diproses serius. Seorang petugas dengan seragam lusuh hanya menggeleng sambil berkata, “Kami akan memproses sesuai prosedur.”
Tapi prosedur itu tak pernah selesai. Dreaningda datang, pergi, datang lagi, dan selalu disambut oleh tembok dingin ketidakpedulian.
Beberapa petugas malah tertawa geli saat mendengar nama Rambaguttah.
“Pak Rambaguttah? Masa sih? Dia kan sering bantu kita pas buka puasa, shalat berjamaah, bikin pengajian.”
Kebaikan palsu yang ditampilkan di layar televisi ternyata lebih meyakinkan daripada jeritan istri yang ditinggalkan tanpa nafkah, tanpa tempat mengadu, dan tanpa satu pun pembela.
=====
Dreaningda akhirnya mengemis keadilan di pinggir jalan. Di trotoar dekat kantor Pocolili, ia duduk dengan membawa karton bertuliskan:
“Aku hanya ingin keadilan untuk anak-anakku. Jangan biarkan topeng menang atas kebenaran.”
Beberapa orang melewati tanpa menoleh. Ada yang mengumpat. Ada yang pura-pura tak melihat. Hanya dua tiga orang yang berhenti, menawarinya air minum, dan kadang uang receh. Tapi bukan uang yang ia butuhkan –melainkan keberanian orang-orang untuk membuka mata pada kemunafikan yang dipelihara.
Suatu hari, seorang pemuda mendekatinya. Namanya Ralofi, seorang mahasiswa hukum dari universitas pinggiran kota. Ia membaca kisah Dreaningda di media sosial, lalu memutuskan untuk mencari kebenarannya sendiri.
“Bu, saya percaya ibu. Saya ingin bantu,” ucapnya singkat.
Dreaningda menatap pemuda itu, tak percaya.
“Mereka semua bilang saya gila…”
“Kadang, satu-satunya orang waras memang terlihat gila di antara kebohongan yang massal,” jawab Ralofi tenang.
Dengan bantuan Ralofi dan dua temannya, Dreaningda mulai mengumpulkan bukti, video, pesan, dokumen pengabaian nafkah, dan semua catatan hotel yang pernah didatangi Rambaguttah. Mereka menyusunnya menjadi berkas panjang yang disebut “Dosa Dalam Jubah Putih”.
Mereka mencoba masuk ke media nasional, tapi ditolak. Tak sedikit jurnalis yang mengaku tidak berani menyentuh “sosok suci” seperti Rambaguttah. Bahkan, ada yang terang-terangan berkata, “Itu berbahaya. Dia punya koneksi.”
Dreaningda menangis lagi. Tapi kali ini bukan karena putus asa. Melainkan karena tekad yang tumbuh semakin kuat. Ia tahu, bila suara tak mampu menembus dinding kekuasaan, maka langkah-langkah kecil di jalanan bisa jadi pukulan besar yang mengguncang dari bawah.
=====
Suatu malam, di tengah hujan deras, ia berdiri di depan gedung Balai Kota Bandroto Ajiancih. Dengan mikrofon kecil dan speaker pinjaman, ia bercerita pada siapapun yang mau berhenti sejenak.
Tentang seorang pria yang fasih berbicara agama tapi membakar keluarganya sendiri. Tentang seorang anak yang bertanya setiap malam, “Kenapa ayah tidak pulang?” Tentang kota keadilan yang tak lebih dari panggung boneka, dikendalikan oleh dalang kotor di belakang layar.
Dan tiba-tiba, sebuah video rekamannya viral.
Hashtag #KeadilanUntukDreaningda menyebar. Banyak orang mulai menghubungkan titik-titik yang selama ini mereka abaikan. Sejumlah wanita diam-diam mengirim pesan ke Ralofi, mengaku pernah menjadi “korban santun” dari Rambaguttah.
Mereka takut, tapi mulai berani bersuara.
=====
Namun, perlawanan pun datang. Ancaman. Fitnah. Serangan digital. Dreaningda disebut agen asing, penghancur moral, penebar hoaks. Tapi ia tidak gentar. Karena kebenaran tak bisa dikalahkan oleh sorak-sorai kepalsuan.
Dan entah kenapa, ia selalu membayangkan suatu hari, dari negeri masa depan, seorang “Superman” akan datang. Bukan dalam jubah biru-merah, tapi mungkin seorang jaksa muda, atau seorang hakim berhati bersih, atau siapa pun dari negeri Mamarika –tempat yang katanya masih peduli pada kebenaran– datang membantunya membawa secercah harapan.
Karena satu hal yang ia yakini: Keadilan mungkin lambat, tapi ia tidak mati.
=====
Dan di bawah langit mendung yang masih menyelimuti Kota Bandroto Ajiancih, Dreaningda berdiri tegak. Ia bukan lagi wanita yang ditinggalkan. Ia adalah suara untuk yang tak bersuara. Luka-luka di hatinya menjadi pelita bagi mereka yang tersesat dalam gelapnya kemunafikan berjubah putih.
Malam itu, Dreaningda duduk di tepi trotoar depan gedung Pocolili yang mulai sepi, memeluk tubuhnya sendiri yang kedinginan. Di depannya, para penegak hukum berlalu-lalang dengan wajah lelah. Mereka lelah bukan karena menegakkan hukum, tapi karena berpura-pura sibuk melakukannya.
Dari balik kaca gedung seberang, jurnalis di negeri kumuh dan penuh kemunafikan itu terlihat sibuk menyunting berita, menghapus nama-nama besar dari daftar pelaku karena “tidak layak tayang” dan “demi menjaga stabilitas.”
Di kafe sebelah, beberapa aktivis tertawa sambil membicarakan rencana demo pekan depan yang disponsori perusahaan besar yang juga menyumbang kekacauan. Seorang pejabat melintas, menunduk bukan karena rendah hati, tapi takut dikenali telah bersalaman dengan pelaku.
Tak jauh dari situ, seorang tokoh agama naik mobil mewah, menyisakan bau parfum Arab yang menyengat tapi tidak cukup kuat untuk menutupi aroma kebusukan kolusi. Sementara sebuah LSM yang dulu sempat memotret Dreaningda untuk konten media sosial, kini bahkan tak lagi menjawab pesannya.
Dreaningda hanya tersenyum kecil. “Lucu,” gumamnya lirih, “ternyata yang paling ramai bicara keadilan adalah mereka yang paling takut keadilan itu benar-benar datang.” Dan malam kembali menelannya, bersama segelintir harapan bahwa esok hari, yang pura-pura tidur akan benar-benar dibangunkan oleh kematian yang penuh kemunafikan, bukan oleh bukan nyanyian atau jepretan kamera wartawan.
======
Disclaimer:
Cerita pendek ini adalah karya fiksi semata. Semua nama tokoh, tempat, peristiwa, dan situasi yang digambarkan dalam cerita merupakan hasil imajinasi penulis dan tidak bermaksud menggambarkan atau menyudutkan individu, lembaga, institusi, atau kelompok mana pun di dunia nyata.
Jika ada kesamaan nama atau kejadian, hal tersebut sepenuhnya kebetulan dan tidak disengaja. Cerpen ini ditulis untuk tujuan sastra dan refleksi sosial semata, bukan sebagai tuduhan atau pernyataan fakta.
Ditulis oleh: Hidayat (Wartawan Media MITRABERITA.NET)