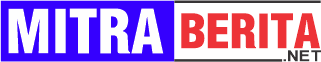MITRABERITA.NET | Angka kemiskinan di Indonesia diklaim mencapai titik terendah dalam dua dekade terakhir. Namun, di balik klaim itu, muncul pertanyaan besar: apakah realitas di lapangan benar-benar mencerminkan data yang disampaikan Badan Pusat Statistik (BPS)?
Sebagai informasi, BPS mencatat jumlah penduduk miskin per Maret 2025 sebesar 23,85 juta orang atau 8,29% dari total populasi nasional Indonesia, mengalami penurunan dibanding periode sebelumnya.
Tetapi bagi sebagian pihak menganggap bahwa angka tersebut justru menyisakan keraguan, terutama dalam hal metodologi pengukuran dan validitas indikator.
Keraguan itu salah satunya diungkapkan Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Esther Sri Astuti. Keraguan itu diungkapkan dalam keterangannya kepada media.
Esther menyebutkan data BPS tidak sepenuhnya mencerminkan kenyataan sosial-ekonomi masyarakat, terutama di tengah gejolak ekonomi pasca pandemi dan maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK) dalam berbagai sektor.
“Karena saat ini kan banyak PHK besar-besaran, terus ketika dibuka lowongan pekerjaan sedikit, malah banyak yang antre. Artinya, ketika saya lihat, garis kemiskinannya itu tidak ter-update,” tegas Esther, seperti dilansir Tirto.id, Sabtu 26 Juli 2025.
Mengacu pada data resmi BPS, garis kemiskinan per Maret 2025 ditetapkan sebesar Rp609.160 per kapita per bulan, atau sekitar Rp20.305 per hari. Namun, bagi Esther, angka ini dianggap terlalu rendah dan tidak lagi mencerminkan kebutuhan riil masyarakat.
“Pendapatan Rp1 juta per bulan pun saat ini belum tentu cukup. Mereka tetap hidup dalam kesulitan, tapi tidak tercatat sebagai miskin menurut definisi BPS,” tambahnya.
Esther juga menyoroti penghitungan kemiskinan masih terlalu sempit, hanya mengandalkan aspek pendapatan tanpa mempertimbangkan indikator multidimensional seperti akses terhadap pendidikan, kesehatan, sanitasi, hingga ketahanan sosial di lingkungan masyarakat.
Ia menyebut angka kemiskinan kerap kali menjadi komoditas politik. Itu sebabnya, ia mendorong pemerintah untuk lebih jujur dan komprehensif dalam menetapkan standar kemiskinan yang relevan dan manusiawi.
“Kami menanti komitmen pemerintah untuk memperbarui ukuran kemiskinan, karena saat ini tidak mencerminkan realitas. Harusnya aspek multidimensional juga diukur,” kata dia.
Esther mencontohkan masyarakat di desa-desa yang secara pendapatan tergolong miskin, namun memiliki akses terhadap sanitasi dan air bersih melalui program gotong royong dan bantuan pemerintah.
Menurutnya, situasi ini menunjukkan bahwa kemiskinan tidak hanya bisa diukur dari nominal penghasilan saja.
Pernyataan kritis ini memicu perdebatan publik soal kebenaran di balik penurunan angka kemiskinan nasional.
Apakah masyarakat Indonesia benar-benar semakin sejahtera, atau hanya terlihat “tidak miskin” karena standar yang digunakan terlalu rendah?
Pertanyaan ini menjadi penting, terutama dalam menilai efektivitas program-program perlindungan sosial dan strategi pengentasan kemiskinan pemerintah.
Jika benar indikatornya tak lagi relevan, maka sudah saatnya pemerintah mengubah pendekatan dan mulai mengadopsi pengukuran kemiskinan multidimensi sebagaimana digunakan oleh banyak negara lain.
Editor: Tim Redaksi