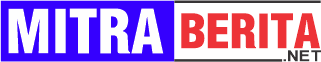ACEH sedang berada di titik krisis yang tidak pernah kita bayangkan akan terjadi lagi setelah dua dekade melewati rekonstruksi tsunami dan rekonsiliasi konflik. Listrik padam berhari-hari, sinyal komunikasi hilang, minyak eceran raib, antrean mengular di seluruh SPBU, tabung gas tak ditemukan, stok makanan untuk korban banjir terbatas, dan distribusi bantuan tersendat bahkan di pusat kota. Satu kalimat yang menggambarkan semuanya: Aceh lumpuh!
Ini bukan lagi sekedar bencana banjir dan longsor. Ini adalah kegagalan sistemik yang membuat masyarakat merasa terisolasi di tengah bencana di tanahnya sendiri. Aceh yang pernah berdiri gagah menghadapi tragedi terbesar pada 2004, kini kembali didera situasi mencekam yang membuka luka lama tentang betapa rentannya kehidupan ketika negara tidak sigap.
Di tengah kegelapan, pertanyaan-pertanyaan publik menggema lebih keras dari suara sirene darurat. Di mana pemerintah? Mengapa listrik padam tanpa kejelasan? Mengapa sinyal mati dan warga tak bisa menghubungi keluarga? Mengapa minyak mendadak hilang di lapak eceran? Mengapa antrian SPBU seperti antre bantuan zaman krisis moneter? Mengapa jalan ke lokasi bencana tidak segera terbuka? Mengapa bantuan lambat dikirim, bahkan untuk daerah yang mudah dijangkau?
Pertanyaan-pertanyaan itu adalah suara rakyat. Suara seorang ibu yang tak bisa membeli gas untuk memasak. Suara seorang ayah yang habis berjam-jam di SPBU hanya untuk setengah tangki bensin. Suara keluarga korban banjir yang menunggu logistik sambil menahan lapar. Dan itu semua adalah suara keputusasaan.
Saat Komunikasi Pemerintah Tumbang
Dalam manajemen bencana, informasi adalah oksigen. Tanpa informasi, masyarakat bernafas dalam kebingungan dan ketakutan. Di sinilah pemerintah seharusnya hadir, bukan sekadar di lapangan, tetapi juga melalui komunikasi publik yang kuat, transparan, dan terstruktur.
Namun yang terjadi justru sebaliknya. Pemerintah tampak sibuk, tetapi publik merasa dibiarkan. Ada laporan internal, rapat penanganan, kunjungan pejabat, tapi tidak ada aliran informasi yang sampai ke masyarakat secara konsisten dan menyeluruh. Hasilnya? Kekosongan informasi yang diisi oleh spekulasi, keresahan, bahkan kepanikan.
Peran humas pemerintah yang seharusnya menjadi garda terdepan komunikasi publik justru terasa paling senyap. Mereka seolah-olah lupa bahwa tulisan ulang pidato pejabat bukanlah komunikasi krisis. Menyebar rilis ke tiga atau empat media bukanlah strategi mitigasi. Dan diam adalah bentuk pengkhianatan terhadap tugas mereka.
Dalam situasi darurat, publik tidak butuh kalimat normatif. Publik butuh kepastian. Publik butuh penjelasan. Publik butuh kehadiran yang terdengar dan terlihat.
Banjir dan longsor adalah bencana alam, iya. Tetapi kekacauan komunikasi, kelangkaan energi, minimnya koordinasi distribusi bantuan, itu bukan bencana alam. Itu adalah bencana administrasi.
Aceh telah melewati konflik 30 tahun lebih, tsunami sangat dahsyat pada tahun 2004, darurat kesehatan Covid-19, harusnya kita sudah punya mental, struktur, dan sistem yang lebih kuat menghadapi krisis. Tetapi realitas memperlihatkan sesuatu yang memalukan: Kita tidak belajar cukup banyak.
Setiap musim hujan datang, kemacetan distribusi bantuan selalu terjadi. Setiap PLN padam, provider otomatis ikut mati. Setiap banjir melanda, jalan terputus berhari-hari tanpa rekayasa cepat yang efektif.
Dan ketika seluruh layanan publik tumbang bersamaan, seperti sekarang, masyarakat akhirnya kembali ke pertanyaan paling sederhana, seberapa siap sebenarnya Aceh menghadapi bencana?
Humas Pemerintah Harus Melek Realitas!
Publik hari ini tidak bisa lagi diperlakukan seperti masyarakat yang hidup di era tahun 1990-an. Saat ini, masyarakat punya akun media sosial. Mereka punya kamera ponsel. Mereka punya suara. Dan yang lebih penting, mereka punya hak untuk tahu informasi.
Humas pemerintah seharusnya menjadi jembatan antara kebijakan dan kepentingan rakyat. Namun selama bencana ini, humas terlihat lebih sibuk menjaga citra pejabat daripada menjaga ketenangan publik. Mereka lebih cepat mengutip pidato pimpinan daripada mengabarkan update lapangan secara real time.
Humas yang tidak memahami fungsi komunikasi krisis bukan hanya gagal, tetapi berpotensi membahayakan. Karena dalam bencana, kekosongan informasi bisa jauh lebih berbahaya daripada banjir itu sendiri. Dan yang penting penting, ketikan listrik PLN padam, provider tidak boleh ikut mati. Ini adalah masalah kronis yang seolah tidak pernah mendapatkan solusi konkret.
Dalam kondisi darurat, provider telekomunikasi wajib memiliki sistem mandiri, mulai dari genset, baterai cadangan, atau teknologi lain yang memungkinkan jaringan tetap hidup meski listrik padam. Jika PLN tersungkur, provider harus tetap berdiri, karena sinyal bukan soal kenyamanan, tapi soal nyawa di era informasi.
Aceh harus mulai mempertanyakan keseriusan provider dalam menyusun mitigasi bencana. Jangan hanya memanen keuntungan saat normal, tapi tumbang tanpa perlawanan saat bencana melanda. Era modern tidak memberi ruang bagi jaringan telekomunikasi yang pasif dan mudah roboh.
Pemerintah Harus Hadir dengan Empati
Aceh tidak membutuhkan pemerintah yang sempurna. Aceh hanya butuh pemerintah yang hadir: Hadir dengan tindakan. Hadir dengan kebijakan jelas. Hadir dengan komunikasi tanpa jeda. Hadir dengan keberanian menghadapi kritik. Dan hadir dengan empati, bukan formalitas dan pencitraan semata.
Di tengah banjir, di tengah gelap, di tengah antrean panjang dan ketidakpastian, masyarakat hanya ingin tahu bahwa mereka tidak sedang sendirian. Bahwa ada negara yang melihat mereka. Bahwa ada pemerintah yang bekerja keras untuk mereka. Jika negara hadir, rakyat akan kuat. Jika negara diam, rakyat akan retak.
Bencana ini seharusnya menjadi alarm terakhir. Kita tidak boleh lagi membiarkan Aceh belajar dari penderitaan berulang kali. Saat semua sistem tumbang secara bersamaan, itu bukan lagi sekadar cobaan alam. Itu tanda bahwa kita harus membenahi akar persoalan. Agar Aceh tidak lagi menjadi daerah yang paling cepat hancur saat badai datang.
Karena seringkali, yang membuat rakyat patah bukan derasnya hujan dan banjir bandang, melainkan gagalnya pemerintahan dalam menjawab pertanyaan dan teriakan mereka. Aceh butuh perubahan. Bukan besok. Bukan lusa. Tapi sekarang!
Ditulis oleh: Hidayat Pulo – Wartawan Muda Aceh