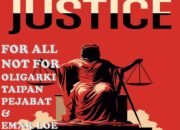ADA kalimat yang kerap diulang di ruang-ruang politik Jakarta yaitu “Korupsi besar tak pernah mati, ia hanya berganti kulit.” Kalimat itu kembali menggema ketika persidangan mantan Direktur Utama Pertamina, Karen Agustiawan, menguak fakta mencengangkan, dimana adanya tekanan dari dua tokoh nasional agar dirinya “memperhatikan perusahaan” milik Moch Riza Chalid (MRC) dan anaknya, Kerry.
Fakta ini tidak muncul dari ruang gelap gosip. Ia diucapkan di hadapan majelis hakim dalam sidang resmi di Pengadilan Tipikor Jakarta pada 27 Oktober 2025. Namun, yang mengejutkan, pernyataan Karen itu tidak dikejar lebih jauh oleh hakim maupun jaksa.
Nama dua tokoh nasional itu, yang menurut hasil penelusuran berinisial PY dan HR, pejabat senior di era pemerintahan SBY menguap begitu saja, tertelan hening yang mencurigakan. Dalam dunia peradilan korupsi, diam kadang lebih berisik dari teriakan.
Kisah Lama yang Tak Usai
Penyidikan kasus mega korupsi Pertamina yang dimulai sejak Oktober 2024 kini memasuki babak baru. Skandal ini bukan sekadar penyimpangan bisnis korporasi negara, melainkan potret utuh dari kolusi antara birokrasi, politik, dan pengusaha rente energi. Berdasarkan hasil audit BPK, total kerugian negara mencapai Rp285,7 triliun, angka yang lebih besar dari anggaran pendidikan nasional tahun berjalan.
Modusnya beragam. Ada ekspor minyak mentah produksi KKKS yang seharusnya bisa dipasok ke kilang Pertamina, tapi justru dijual ke luar negeri melalui perusahaan perantara. Ada pula skema HIP blending Pertalite yang diusulkan Dirut PT Patra Niaga Alfian Nasution dan Direktur Mars Ega Legowo Putra melalui Dirut Pertamina Nicke Widyawati kepada Menteri ESDM, yang berujung kerugian Rp11,11 triliun.
Belum lagi kasus kompensasi BBM Pertalite Ron 90 untuk 2022-2023 senilai Rp13,118 triliun, serta penjualan solar industri di bawah harga subsidi kepada 13 perusahaan, termasuk PT Adaro milik Boy Thohir, yang menimbulkan kerugian Rp9,4 triliun.
Kisah ini memperlihatkan bahwa Pertamina telah lama menjadi arena tarung kekuasaan, tempat di mana pejabat, pengusaha, dan penegak hukum saling menukar kepentingan. Ketika minyak menjadi sumber kekuatan politik, maka kebocoran anggaran bukan lagi kecelakaan administratif, melainkan konsekuensi dari sistem yang sengaja diciptakan untuk bocor.
Dalam catatan, MRC bukan nama asing. Ia dikenal di kalangan pelaku bisnis migas sebagai “raja minyak belakang layar”, pemain lama yang bertahun-tahun menguasai jalur impor dan distribusi bahan bakar melalui jaringan perusahaannya di dalam dan luar negeri. Dalam beberapa laporan, disebutkan bahwa MRC pernah memiliki hubungan bisnis dengan sejumlah perusahaan yang menjadi mitra strategis Pertamina.
Beberapa sumber di internal penegak hukum mengungkap bahwa sebelum penetapan tersangka, MRC sempat beberapa kali bertemu dengan seorang makelar kasus (markus) di Kuala Lumpur. Pertemuan itu diduga berkaitan dengan upaya melobi agar kasusnya tidak naik ke tahap penyidikan. Dugaan semacam ini, bila benar, menunjukkan bahwa korupsi di negeri ini bukan hanya soal uang negara yang raib, tetapi juga tentang mata rantai impunitas yang dibiarkan hidup di jantung lembaga hukum.
Bayang Negara di Balik Negara
Korupsi BUMN seperti Pertamina adalah cermin dari apa yang disebut filsuf politik Niccolò Machiavelli sebagai “negara di balik negara”, sebuah jaringan kekuasaan informal yang hidup di bawah permukaan birokrasi formal. Dalam jaringan ini, keputusan tidak lagi ditentukan oleh regulasi atau kepentingan publik, melainkan oleh negosiasi antar elit, memo-memo pribadi, dan tekanan politik yang tak tercatat dalam notulen rapat resmi.
Dugaan adanya memo tahun 2015 yang ditandatangani SN, kala itu Ketua DPR RI, kepada Direksi Pertamina agar membayar invoice PT Orbit Terminal Merak meski KPK telah memberi sinyal adanya pelanggaran, menambah lapisan gelap dari praktik ini. Memo itu bukan sekadar surat, ia adalah simbol bagaimana kekuasaan legislatif bisa menjadi pintu masuk intervensi bisnis.
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN jelas menyebut bahwa direksi wajib mengelola perusahaan dengan prinsip profesional, efisien, transparan, dan akuntabel. Tapi dalam praktiknya, prinsip itu sering tersandera oleh perintah politik. Sejak lama, kursi direksi BUMN menjadi bagian dari bargaining politik dalam kabinet. Maka tak heran bila kebijakan bisnis sering kali dijalankan bukan berdasarkan analisis ekonomi, melainkan pesanan kekuasaan.
Di sinilah letak paradoks pembangunan ekonomi nasional. Negara mendirikan BUMN untuk menjaga kedaulatan ekonomi, namun BUMN justru menjadi alat bagi sekelompok elit untuk mempertahankan kedaulatan pribadi.
Ketika Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Jaksa Agung untuk menuntaskan kasus korupsi di BUMN tanpa tebang pilih, publik menaruh harapan besar. Tetapi harapan itu akan segera berubah menjadi sinisme bila penyidikan berhenti pada level teknokrat, tanpa menyentuh mereka yang berada di lingkaran politik tertinggi. Sebab publik sudah terlalu sering melihat pola lama: kasus besar dimulai dengan gegap gempita, berakhir dengan kompromi di ruang senyap.
Korupsi Sebagai Struktur Kekuasaan
Dalam ilmu politik modern, korupsi tidak lagi dipandang sekadar penyimpangan individu, melainkan bagian dari struktur kekuasaan yang menciptakan loyalitas dan stabilitas politik. Di negara-negara berkembang, korupsi sering menjadi “pelumas sistem”, alat bagi elit untuk menjaga harmoni semu antar kelompok kepentingan.
Indonesia pun tidak sepenuhnya lepas dari logika ini. Korupsi di BUMN migas menciptakan jaringan rente yang luas: dari pejabat kementerian, komisaris, hingga kelompok usaha yang menjadi mitra strategis. Dalam situasi semacam ini, pemberantasan korupsi bukan hanya soal moralitas, melainkan soal keberanian politik untuk menabrak tembok oligarki.
Kasus Pertamina menunjukkan bahwa hukum sering berhenti di batas yang aman secara politis. Karen Agustiawan memang diadili, namun tekanan politik yang ia alami, yang bisa membuka tabir keterlibatan tokoh-tokoh besar justru tidak diselidiki lebih jauh. Padahal, dalam sistem hukum modern, kesaksian di bawah sumpah adalah pintu masuk utama bagi pembuktian jaringan kejahatan.
Jika keterangan semacam itu diabaikan, maka publik berhak bertanya, apakah hukum masih bekerja untuk kebenaran, atau hanya untuk memelihara keseimbangan kekuasaan?
Energi, Nasionalisme, dan Harga Sebuah Kebenaran
Sektor energi selalu menjadi urat nadi kedaulatan bangsa. Dalam visi pembangunan nasional, kemandirian energi seharusnya menjadi pilar utama untuk mencapai keadilan sosial dan kedaulatan ekonomi. Namun, ketika tata kelola sektor ini disandera oleh kepentingan politik jangka pendek, maka cita-cita nasionalisme ekonomi pun kehilangan makna.
Kita mungkin telah kehilangan terlalu banyak berupa kepercayaan publik, uang negara, bahkan integritas lembaga penegak hukum. Tapi yang paling berbahaya adalah hilangnya rasa gentar terhadap dosa kekuasaan. Jika tekanan politik terhadap direksi BUMN dianggap hal biasa, dan markus menjadi perantara legal di balik layar, maka korupsi tak lagi sekadar kejahatan, melainkan kebiasaan negara.
Presiden Prabowo, dalam pidatonya awal tahun ini, menyebut akan “menebas siapa pun yang mengkhianati negara demi uang”. Pernyataan itu menggugah. Tapi dalam politik, keberanian sejati bukanlah pada kata-kata, melainkan pada keputusan menindak mereka yang paling dekat dengan lingkar kekuasaan sendiri.
Kini bola panas itu berada di tangan Jaksa Agung dan tim Jampidsus. Apakah mereka berani menelusuri nama-nama besar seperti yang disebut Karen Agustiawan? Apakah mereka berani mengungkap peran mantan Menteri BUMN Erick Thohir atau bahkan mengevaluasi kebijakan era Presiden Jokowi yang diduga memberi perlindungan kepada MRC?
Publik tidak menuntut balas dendam, hanya keadilan yang utuh dan setara di hadapan hukum. Sejarah telah memberi cukup banyak pelajaran bahwa bangsa ini tidak akan runtuh karena musuh di luar, melainkan karena kompromi di dalam.
Korupsi di sektor energi bukan sekadar soal angka, melainkan soal masa depan bangsa. Setiap liter minyak yang dijual di bawah harga pasar, setiap memo politik yang menekan direksi, setiap pertemuan gelap antara pengusaha dan markus, semuanya adalah luka bagi republik ini.
Di tengah kabut manipulasi dan kekuasaan, publik menunggu satu hal: keberanian untuk menyalakan nyala kebenaran, sekecil apa pun itu. Karena pada akhirnya, bangsa ini hanya akan benar-benar merdeka bila berani menegakkan hukum di atas segala nama besar.
Ditulis oleh: Sri Radjasa, MBA (Pemerhati Intelijen)