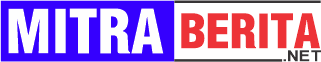PASCA kerusuhan Agustus Kelabu, muncul tuntutan populer yang dikenal sebagai “17+8”. Salah satu butir yang paling disuarakan adalah desakan agar TNI kembali ke barak, mencabut mandat mereka dari berbagai proyek sipil, sekaligus merevisi UU TNI.
Seruan itu datang dari kalangan yang mengklaim diri sebagai civil society, tetapi lebih menyerupai gema dendam politik masa lalu ketimbang refleksi jernih atas perjalanan reformasi dua dekade terakhir.
Sejak 1998, reformasi TNI telah melewati jalan panjang berupa penghapusan dwi fungsi ABRI, penarikan peran dari parlemen, hingga restrukturisasi internal yang menempatkan supremasi sipil sebagai pakem utama.
Literatur akademik, dari Crouch hingga Mietzner, mencatat bahwa Indonesia adalah salah satu negara di Asia Tenggara yang berhasil menekan dominasi militer di ranah politik. Namun, jargon “TNI kembali ke barak” terus diulang, seolah menjadi mantra untuk memasung peran TNI dalam kehidupan kebangsaan.
Padahal, TNI tidak lahir dari rahim kekuasaan otoriter semata. Ia tumbuh dari pergulatan rakyat melawan kolonialisme, dari tradisi perang gerilya hingga menjadi kekuatan inti dalam doktrin sistem pertahanan rakyat semesta.
Jati diri TNI sebagai tentara rakyat, tentara pejuang, dan tentara nasional yang menjadikannya entitas unik dibandingkan militer negara lain. Menghapus peran sosial TNI secara total sama saja menafikan akar sejarah yang meneguhkan relasi erat mereka dengan rakyat.
Tentu, periode Orde Baru adalah bab kelam berupa dominasi politik militer, represi kebebasan sipil, hingga kontrol ekonomi yang meluas. Tetapi koreksi sudah dilakukan lewat reformasi. Menuntut amputasi peran TNI secara total, hingga sekadar menjadi penonton ketika rakyat diperas oleh oligarki sipil, sama berbahayanya dengan kembalinya dwifungsi di masa lalu.
Di sisi lain, klaim supremasi mengatasnamakan sipil pasca reformasi ternyata melahirkan paradoks. Alih-alih memperkuat demokrasi, kita menyaksikan menguatnya otoritarianisme sipil. Selama dua periode pemerintahan Presiden Joko Widodo, energi bangsa terkuras pada kebijakan pembangunan yang rapuh fondasinya, politik dinasti yang menggerus etika demokrasi, serta penegakan hukum yang berubah menjadi instrumen represi.
Data Bank Indonesia mencatat lonjakan utang luar negeri hingga menembus 400 miliar dolar AS, sementara Transparency International menempatkan Indonesia pada skor Indeks Persepsi Korupsi 34 persen tak jauh dari era Orde Baru.
Dalam situasi inilah, sebagian aktivis sipil dan influencer digital justru memilih menjadikan TNI sebagai kambing hitam. Nama-nama seperti Ferry Irwandi dan kawan-kawan, dengan modal literasi digital, menggaungkan tuduhan seakan keterpurukan bangsa ini bersumber dari bayang-bayang militerisme. Ironisnya, mereka menutup mata terhadap kerusakan tata kelola sipil yang nyata terjadi selama sepuluh tahun terakhir.
Generasi muda yang menguasai ruang publik seharusnya mampu menggunakan nalar dan nurani. Objektivitas menuntut keberanian menyebut sumber masalah yaitu kegagalan kepemimpinan sipil dalam mengelola demokrasi dan ekonomi.
Gus Dur pernah berujar, Indonesia bukan negara demokratis, bukan pula negara sekuler tetapi Indonesia adalah “negara yang bukan-bukan.” Ungkapan itu seakan relevan hari ini, bangsa ini tengah terjebak di antara ilusi demokrasi dan otoritarianisme sipil.
Menuntut TNI kembali ke barak tanpa evaluasi jujur terhadap kegagalan sipil hanya melanggengkan arogansi politik sipil itu sendiri. Reformasi seharusnya bukan amputasi, melainkan keseimbangan: TNI tetap tunduk pada supremasi sipil, tetapi tidak dijauhkan dari rakyat dan tanggung jawab sejarahnya. Jika sipil gagal mengelola demokrasi, jangan lagi mencari kambing hitam ke arah tentara.
Ditulis oleh : Sri Radjasa, M.BA (Pemerhati Intelijen)