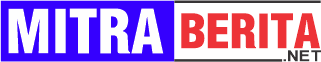DALAM dunia politik, diam sering dipuji sebagai tanda kedewasaan, kesabaran, atau strategi diplomasi yang cermat. Namun, ketika diam dipraktikkan di hadapan genosida, maknanya berubah total. Ia bukan lagi simbol kebijaksanaan, melainkan bentuk keterlibatan pasif dalam kejahatan itu sendiri. Gaza adalah buktinya!
Selama lebih dari tujuh dekade, rakyat Palestina hidup dalam penderitaan di bawah pendudukan dan kekerasan sistematis yang dilakukan oleh Israel. Generasi demi generasi tumbuh dalam reruntuhan rumah yang dibom, sekolah yang dihancurkan, dan harapan yang dipangkas. Namun, puncak tragedi ini terjadi sejak Oktober 2023, ketika gelombang serangan militer Israel ke Jalur Gaza memicu krisis kemanusiaan yang oleh banyak pihak, termasuk pakar PBB dan lembaga HAM internasional, disebut sebagai genosida.
Ironisnya, di tengah teriakan pilu warga Gaza yang disiarkan ke seluruh dunia, sebagian besar pemimpin dunia justru memilih diam. Diam yang mereka bungkus dengan istilah “keprihatinan”, “diplomasi tenang”, atau “menunggu momentum yang tepat”. Diam yang di satu sisi terdengar halus, namun di sisi lain, mematikan.
Data yang dirilis berbagai media dan lembaga internasional sudah cukup untuk menggugah hati siapa pun. Hingga pertengahan 2025, jumlah korban tewas di Gaza dilaporkan melampaui 60.000 jiwa, hampir separuhnya adalah perempuan dan anak-anak.
Angka ini berarti rata-rata 91 nyawa hilang setiap hari. Korban luka traumatik mencapai lebih dari 100.000 jiwa, dengan banyak yang harus menjalani amputasi tanpa obat bius karena kelangkaan peralatan medis.
The Lancet, jurnal medis terkemuka, memperkirakan bahwa jumlah kematian sebenarnya bisa lebih tinggi karena banyak jenazah yang tidak pernah ditemukan di bawah puing-puing bangunan. Bahkan, The Guardian mengingatkan bahwa angka resmi yang dirilis mungkin hanya “puncak dari gunung es”.
Tidak berhenti di situ, Gaza kini juga menghadapi krisis kelaparan terburuk abad ini. Panel ahli PBB melaporkan lebih dari sepertiga anak-anak menderita malnutrisi akut, dan dalam satu pekan terakhir saja tercatat 79 kematian akibat kelaparan. Blokade bantuan kemanusiaan, penghancuran gudang pangan, dan penutupan perlintasan membuat akses terhadap makanan dan air bersih menjadi nyaris mustahil
Tudingan Genosida yang Semakin Kuat
Pada November 2024, Komite Khusus PBB secara resmi menyatakan bahwa metode perang Israel termasuk penggunaan kelaparan sebagai senjata perang konsisten dengan unsur-unsur genosida. Pernyataan serupa datang dari para ahli HAM PBB yang memperingatkan bahwa jika komunitas internasional tidak bertindak, dunia akan menjadi saksi genosida yang “berlangsung di depan mata kita.”
Yang mengejutkan, suara keras itu tidak hanya datang dari luar Israel. Dua organisasi HAM terkemuka di dalam negeri, B’Tselem dan Physicians for Human Rights-Israel, menjadi yang pertama secara terbuka menuduh pemerintah mereka melakukan kampanye terencana untuk menghancurkan rakyat Palestina. Mereka menyebut operasi militer ini sebagai “serangan sistematis terhadap kehidupan sipil yang tak bisa dijustifikasi.”
Dengan bukti yang begitu melimpah, foto satelit kehancuran, video serangan terhadap rumah sakit, laporan investigasi media, dan testimoni korban, narasi bahwa ini sekadar “konflik” semakin sulit dipertahankan. Dunia tahu ini adalah pembantaian yang disengaja.
“Diam” Sebagai Kebijakan
Meski bukti menumpuk, reaksi negara-negara besar justru sering terjebak dalam politik bahasa. Beberapa sekutu Israel, seperti Amerika Serikat dan Inggris, tetap memberikan dukungan militer dan politik, sambil sesekali menyerukan “gencatan senjata sementara”. Uni Eropa terbelah; sebagian negara mendesak sanksi, sementara yang lain memilih tak mengubah kebijakan.
Ada pula negara yang mulai menunjukkan tanda perubahan. Jerman, misalnya, baru-baru ini menghentikan ekspor senjata ke Israel, sebuah langkah berani mengingat hubungan historis dan politik kedua negara. Namun, tindakan ini masih minor dibanding skala tragedi.
Mayoritas pemimpin dunia tampak nyaman berada di wilayah abu-abu: mengutuk kekerasan secara umum, tapi menghindari menyebut pelaku secara langsung; mengumumkan bantuan kemanusiaan, tapi tidak menekan secara politik; berbicara tentang “solusi dua negara”, tapi membiarkan satu negara terus memperluas pendudukannya.
Diam di sini bukanlah kebetulan. Diam adalah kebijakan. Diam adalah cara “aman” untuk menghindari risiko diplomatik, mempertahankan aliansi strategis, dan melindungi kepentingan ekonomi.
Harga dari Kebisuan Dunia
Bagi rakyat Gaza, kebisuan dunia terasa seperti pengkhianatan. Mereka tidak hanya menghadapi rudal dan peluru, tetapi juga dinding tak kasat mata berupa apatisme internasional. Setiap kali pemimpin dunia memilih diam, itu berarti memberi waktu lebih lama bagi mesin perang untuk bekerja.
Diam juga memberi ruang bagi narasi palsu untuk berkembang. Dengan media internasional dilarang masuk ke Gaza, sebagaimana diungkapkan otoritas media setempat, dunia luar bergantung pada potongan-potongan informasi yang sering dimanipulasi. Sementara itu, korban terus bertambah tanpa liputan memadai.
Sejarah mengajarkan bahwa kebisuan di hadapan kejahatan kemanusiaan selalu berujung pada penyesalan. Kita melihatnya di Rwanda, Bosnia, dan banyak tragedi lain. Pertanyaannya: apakah Gaza akan menjadi satu lagi bab dalam buku sejarah yang penuh dengan kalimat “seandainya dunia bertindak lebih cepat…”?
Diam Adalah Persetujuan
Sebagian orang mungkin berpendapat bahwa diam adalah bentuk netralitas atau langkah sementara sebelum intervensi. Namun, dalam situasi genosida, diam justru adalah persetujuan. Ia adalah sinyal kepada pelaku bahwa dunia tidak akan benar-benar menghentikan mereka.
Pemimpin dunia mungkin menganggap mereka “bermain aman” dengan tidak bersuara lantang. Namun, aman bagi siapa? Aman bagi hubungan dagang, kontrak senjata, dan citra diplomatik, tapi jelas tidak aman bagi anak-anak di Gaza yang tidur dalam kegelapan, lapar, dan ketakutan akan serangan berikutnya.
Penting diingat, diam bukanlah ruang hampa. Diam adalah pesan. Dan dalam konteks ini, pesannya jelas: penderitaan rakyat Palestina dianggap bisa dinegosiasikan; nyawa mereka tidak memiliki nilai politik yang cukup besar untuk memicu tindakan tegas.
Mengganti Diam dengan Tindakan
Mungkin masih ada waktu untuk mengubah jalannya sejarah. Tekanan publik global telah beberapa kali memaksa pemerintah untuk mengubah sikapnya. Aksi boikot, unjuk rasa besar-besaran, dan kampanye digital menunjukkan bahwa suara rakyat biasa bisa menembus tembok kebisuan politik.
Namun, selama para pemimpin dunia terus memelihara budaya diam dengan sejuta alasan, penderitaan di Gaza akan berlanjut. Anak-anak akan terus tumbuh dengan trauma, keluarga akan terus tercerai-berai, dan dunia akan semakin kehilangan moralnya.
Sejarah tidak akan bertanya siapa yang “bersikap netral” di masa ini. Sejarah akan membagi tokohnya menjadi dua: mereka yang berusaha menghentikan genosida, dan mereka yang membiarkannya terjadi.
Dan satu hal pasti: di hadapan genosida, diam bukanlah emas, diam adalah darah yang mengalir di tangan kita semua yang ikut andil dalam genosida Gaza.
Ditulis oleh: Hidayat (Wartawan Media MITRABERITA.NET)